"To be effective is the job of the executive.‘To effect’ and ‘to execute’ are, after all, near–synonyms.
Whether he works in a business or in a hospital,in government agency or in the a labor union,in a university of tin the army,the executive is , first of all, expected to get the right things done.And this is simply that he is expected to be effective.”
– Peter Drucker, 1967 –
Ada sementara literatur yang memisahkan dengan tegas pola pikir “manajer” dengan pola pikir “leader”. Konon, manajer berpikir to do things right, sedangkan leader berpikir to do the right things. Pembedaan tersebut sebenarnya boleh juga untuk mempertajam pengertian, karena memang sebuah kontras biasanya membuat kita lebih mudah memahami dan kemudian mengingat suatu konstruksi konseptual. Namun demikian, setelah dipikir lebih mendalam, sulit bagi kita membuat dikotomi sesederhana itu. Untuk menjalankan perannya dengan efektif, yaitu menggerakkan proses transformasi, di samping menjadikan concern-nya terhadap people dan contribution menjadi bermakna dan produktif, bagaimanapun seorang pemimpin perlu menghayati manajemen sebagai paradigma berpikir.
Dengan demikian rasanya what is management menjadi perlu untuk dijawab terlebih dahulu. Beragam definisi bisa dikemukakan. Ada yang mengatakan management is an art and a science – manajemen adalah seni dan ilmu. Ada juga yang bilang management is getting things done through and with other people. Kumpulkan 100 buku manajemen, besar kemungkinan lebih dari 100 definisi bisa kita koleksi.
Mari sedikit usil menguji validitas berbagai definisi tersebut. Sebelumnya perhatikan analogi berikut ini. Misal, kita diminta membuat definisi mengenai “mahasiswa yang pintar”. Lalu kita jawab, “mahasiswa yang pintar adalah mahasiswa yang mampu lulus tepat waktu dengan IPK minimum 3.” Definisi yang cukup masuk akal dan dapat diterima. Nah, sekarang, jika kita diminta membuat definisi mengenai “mahasiswa yang tidak pintar,” dengan relatif mudah kita bisa menjawab menggunakan definisi yang telah kita buat sebelumnya sebagai dasar. “Mahasiswa yang tidak pintar adalah mahasiswa yang terlambat lulus dengan IPK di bawah 3.”
Misalkan Anda percaya bahwa management is an art and a science. Tolong bantu kita untuk menjelaskan what is mismanagement. Ingat, Anda harus gunakan definisi tersebut sebagai dasar. Maka, management is … ? Apakah bisa kita katakan, management is not an art and not a science? Rasanya tidak. Kesimpulannya, macet! Silakan coba keisengan seperti ini dengan berbagai definisi lainnya tentang manajemen. Saya pernah mencobanya. Berkali-kali. Dan hasilnya kurang lebih sama: macet.
Saya mencoba mencari tahu jawaban mengapa demikian. Dan rasanya jawaban itu sudah saya temukan. Intinya, manajemen tampaknya lebih merupakan “makhluk praktis” ketimbang “makhluk akademis.” Karena itu, memahami manajemen melalui “teropong akademis,” seperti membuat definisi, misalnya, akan membuat urusan kita menjadi agak kusut. Sebaliknya, menggunakan cara praktis, semisal membuat “rambu-rambu” mungkin akan lebih sederhana, fungsional dan memudahkan dalam memahami manajemen sebagai paradigma berpikir.
Paling tidak ada lima rambu manajemen. Pertama, proses. Ya, sesuatu disebut manajemen jika ia adalah sebuah proses. Ada dimensi ruang dan waktu. Ada pentahapan. Ada pergerakan dan perubahan. Melibatkan input yang diolah sedemikian rupa untuk menjadi output. Ada mekanisme dan prosedur. Tidak instant. Tidak kenal istilah “pokoknya.” Seorang anak kecil tentu saja belum memahami, apalagi menghayati, manajemen sebagai paradigma berpikir. Karena itu, ketika ia ingin memiliki mainan baru seperti miliki temannya, ia spontan berkata, “Pokoknya aku ingin mainan yang itu sekarang!” Kalaulah orangtuanya berkata, “Sabar ya nak. Ayah kan belum ada uang. Bulan depan ya,” jawaban sang anak, “Nggak mau! Pokoknya sekarang!” Nah, terbukti, alpanya pola pikir manajemen membuat interaksi kita dengan orang lain macet total.
Walaupun kondisi dalam contoh di atas dapat dimaklumi, karena pelakunya anak kecil. Namun jangan salah, mismanagement dalam proses berpikir yang esensinya sama tak kurang banyaknya diidap oleh orang usianya sudah dewasa bahkan tua atau senja. Korupsi misalnya, adalah perilaku kotor yang salah satu akarnya adalah penyakit kronis berpikir instan model “pokoknya saya ingin kaya sekarang juga.” Jadi, dilihat dari kacamata agama, korupsi adalah dosa besar. Dari kacamata hukum positif, korupsi adalah pelanggaran pidana berat (walaupun sering diringan-ringankan). Sedangkan dari kacamata manajemen, korupsi adalah mismanagement!
“In the last analysis management is practice.
Its essence is not knowing, but doing.
Its test is not logic, but result.
Its only authority is performance”
– Peter Drucker –
Si Fulan yang punya toko kelontong lelah hidup seadanya. Ia ingin agar dagangannya laris-manis, agar ia segera “naik kelas” menjadi orang kaya. Atas saran beberapa teman sekampung ia pergi ke sebuah dusun di kaki Gunung Lawu, menemui seorang dukun yang konon sakti mandraguna. Dukun itu merapal beberapa mantra. Tentunya ditingkahi oleh asap kemenyan dan suasana magis yang mencekam. Si Fulan juga dititahkan untuk mandi kembang tujuh rupa, di samping dioleh–olehi beberapa jenis jimat. Ternyata “proses” yang dijalani si Fulan memang ampuh. Tak berapa lama orang berbondong-bondong membeli dagangannya. Dapatkah dikatakan si Fulan telah menerapkan manajemen? Tentu tidak. Bukankah ia telah menempuh proses? Ya. Bahkan proses yang lumayan “serius” dan “berat.”
Namun proses bukanlah satu-satunya rambu manajemen. Ada rambu yang kedua, yaitu sistematis dan logis. Bisa saja, walaupun agak dipaksakan, dikatakan bahwa proses yang dilalui oleh Fulan bersifat sistematis. Namun bagaimanapun tidak logis. Logika ilmu pengetahuan, kecuali ilmu sihir tentunya, tidak dapat menjelaskan apa hubungannya merapal mantra, mandi kembang, mempersembahkan sesajian, atau menyimpan jimat, dengan perniagaan si Fulan yang jadi marak dan meriah. Bahkan sistematis pun sebenarnya tidak. Karena resep yang diberikan si mbah dukun kepada si Fulan konon tergantung pada apa yang dibisikkan para peliharaannya ketika si Fulan menghadap. Artinya, kalau di kemudian hari ada pasien lain, walaupun dengan kebutuhan yang sama, sangat boleh jadi si mbah akan menuturkan jalan keluar yang berbeda. Intinya, tak ada pola yang menghubungkan antara keluhan pasien dengan treatment yang diberikan. Dalam kacamata agama, perbuatan si Fulan adalah syirik. Dalam sudut pandang manajemen, ini lagi-lagi bentuk mismanagement!
Dalam kehidupan sehari-hari yang lebih umum kita lihat betapa banyak masalah, kekusutan, kekacauan, kesimpang-siuran yang membuat masyarakat kehilangan kebahagiaan, ternyata bersumber dari proses – bentuknya bisa berupa sistem, mekanisme, prosedur, aturan, dan lain-lain – yang tidak sistematis (baca: acak-acakan, melompat-lompat, tidak punya alur yang masuk akal), dan juga tidak cukup ditopang oleh dasar logika yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa waktu yang lalu saya punya tugas mengisi training di Surabaya. Sayangnya saya terlambat tiba di check-in counter Bandara Soekarno–Hatta karena taksi yang saya tumpangi mengalami pecah ban di jalan tol. Karena belum pernah mengalami hal tersebut sebelumnya, saya bertanya kepada petugas dari airline terkait mengenai apa yang semestinya saya lakukan. Hasilnya, saya pusing! Saya di ping-pong dari satu counter ke counter yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu loket ke loket yang lain. “Coba bicara pada Mbak yang di sana Pak.” “Coba ke loket reservasi Pak.” “Coba ke counter nomor 24 Pak.” Astagfirullah! Mbak yang bertugas di loket reservasi melayani saya dengan wajah galak, suara ketus, dan gaya setengah hati. “Pak, karena terlambat, jika Bapak ingin dimasukkan ke flight berikutnya Bapak terkena denda 75% dari harga tiket plus biaya up-grade sebesar sekian rupiah, sehingga totalnya sekian rupiah. Nanti dibayar di counter 24.” What?! Lebih dari dua kali lipat harga tiket saya sebelumnya!
Lalu, sesuai petunjuk si Mbak yang “pedas” itu saya kembali ke counter 24. Mbak yang ada di sana – paling tidak dia jauh lebih ramah – menanyakan berapa biaya tambahan yang dikenakan pada saya. Mendengar jumlah yang saya sebutkan, Mbak yang ramah itu berkata, “Wah, Bapak tidak perlu bayar sejumlah itu. Cukup setengahnya saja kepada kami. Di sini nama Bapak sudah saya tuliskan. Dan statusnya sudah saya buat CF (confirmed) untuk penerbangan berikut jam 13:30. Bapak tinggal datang. Sebutkan nama, bayar, dan berangkat.” Ajaibnya, pada saat saya datang lagi ke counter 24 menjelang pukul 13:30 “Miss Ramah” itu tak ada di sana, dan nama saya tidak tercantum di dalam daftar cadangan, apalagi dengan status confirmed. Macet bukan?! Alhasil, saya gagal berangkat ke Surabaya pada hari itu.
Mari kita bayangkan, apa derita umat, masyarakat, dan bangsa, jika mereka yang berada dalam posisi memimpin tidak punya kemampuan berpikir proses secara sistematis dan logis? Ya, mungkin mirip sekali seperti kondisi kita hari-hari ini.
“Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dari cara–cara yang sama.”
–anonimus–
Saya punya suatu kepercayaan sederhana mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Bagi saya, kualitas kepemimpinan seorang pemimpin diukur dari karya, bukan orasi atau wacana, walaupun kemampuan berorasi mungkin salah satu skill penting bagi pemimpin. Lihat saja pernyataan Allah SWT di dalam Al Qur-an: “Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu.’ Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” [QS. At-Taubah, 9: 105]
وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾
Simak juga peringatan keras Allah SWT di bagian lain dari Kitab Suci-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” [QS. Ash-Shaff, 61: 2-3]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾
Whether he works in a business or in a hospital,in government agency or in the a labor union,in a university of tin the army,the executive is , first of all, expected to get the right things done.And this is simply that he is expected to be effective.”
– Peter Drucker, 1967 –
Ada sementara literatur yang memisahkan dengan tegas pola pikir “manajer” dengan pola pikir “leader”. Konon, manajer berpikir to do things right, sedangkan leader berpikir to do the right things. Pembedaan tersebut sebenarnya boleh juga untuk mempertajam pengertian, karena memang sebuah kontras biasanya membuat kita lebih mudah memahami dan kemudian mengingat suatu konstruksi konseptual. Namun demikian, setelah dipikir lebih mendalam, sulit bagi kita membuat dikotomi sesederhana itu. Untuk menjalankan perannya dengan efektif, yaitu menggerakkan proses transformasi, di samping menjadikan concern-nya terhadap people dan contribution menjadi bermakna dan produktif, bagaimanapun seorang pemimpin perlu menghayati manajemen sebagai paradigma berpikir.
Dengan demikian rasanya what is management menjadi perlu untuk dijawab terlebih dahulu. Beragam definisi bisa dikemukakan. Ada yang mengatakan management is an art and a science – manajemen adalah seni dan ilmu. Ada juga yang bilang management is getting things done through and with other people. Kumpulkan 100 buku manajemen, besar kemungkinan lebih dari 100 definisi bisa kita koleksi.
Mari sedikit usil menguji validitas berbagai definisi tersebut. Sebelumnya perhatikan analogi berikut ini. Misal, kita diminta membuat definisi mengenai “mahasiswa yang pintar”. Lalu kita jawab, “mahasiswa yang pintar adalah mahasiswa yang mampu lulus tepat waktu dengan IPK minimum 3.” Definisi yang cukup masuk akal dan dapat diterima. Nah, sekarang, jika kita diminta membuat definisi mengenai “mahasiswa yang tidak pintar,” dengan relatif mudah kita bisa menjawab menggunakan definisi yang telah kita buat sebelumnya sebagai dasar. “Mahasiswa yang tidak pintar adalah mahasiswa yang terlambat lulus dengan IPK di bawah 3.”
Misalkan Anda percaya bahwa management is an art and a science. Tolong bantu kita untuk menjelaskan what is mismanagement. Ingat, Anda harus gunakan definisi tersebut sebagai dasar. Maka, management is … ? Apakah bisa kita katakan, management is not an art and not a science? Rasanya tidak. Kesimpulannya, macet! Silakan coba keisengan seperti ini dengan berbagai definisi lainnya tentang manajemen. Saya pernah mencobanya. Berkali-kali. Dan hasilnya kurang lebih sama: macet.
Saya mencoba mencari tahu jawaban mengapa demikian. Dan rasanya jawaban itu sudah saya temukan. Intinya, manajemen tampaknya lebih merupakan “makhluk praktis” ketimbang “makhluk akademis.” Karena itu, memahami manajemen melalui “teropong akademis,” seperti membuat definisi, misalnya, akan membuat urusan kita menjadi agak kusut. Sebaliknya, menggunakan cara praktis, semisal membuat “rambu-rambu” mungkin akan lebih sederhana, fungsional dan memudahkan dalam memahami manajemen sebagai paradigma berpikir.
Paling tidak ada lima rambu manajemen. Pertama, proses. Ya, sesuatu disebut manajemen jika ia adalah sebuah proses. Ada dimensi ruang dan waktu. Ada pentahapan. Ada pergerakan dan perubahan. Melibatkan input yang diolah sedemikian rupa untuk menjadi output. Ada mekanisme dan prosedur. Tidak instant. Tidak kenal istilah “pokoknya.” Seorang anak kecil tentu saja belum memahami, apalagi menghayati, manajemen sebagai paradigma berpikir. Karena itu, ketika ia ingin memiliki mainan baru seperti miliki temannya, ia spontan berkata, “Pokoknya aku ingin mainan yang itu sekarang!” Kalaulah orangtuanya berkata, “Sabar ya nak. Ayah kan belum ada uang. Bulan depan ya,” jawaban sang anak, “Nggak mau! Pokoknya sekarang!” Nah, terbukti, alpanya pola pikir manajemen membuat interaksi kita dengan orang lain macet total.
Walaupun kondisi dalam contoh di atas dapat dimaklumi, karena pelakunya anak kecil. Namun jangan salah, mismanagement dalam proses berpikir yang esensinya sama tak kurang banyaknya diidap oleh orang usianya sudah dewasa bahkan tua atau senja. Korupsi misalnya, adalah perilaku kotor yang salah satu akarnya adalah penyakit kronis berpikir instan model “pokoknya saya ingin kaya sekarang juga.” Jadi, dilihat dari kacamata agama, korupsi adalah dosa besar. Dari kacamata hukum positif, korupsi adalah pelanggaran pidana berat (walaupun sering diringan-ringankan). Sedangkan dari kacamata manajemen, korupsi adalah mismanagement!
“In the last analysis management is practice.
Its essence is not knowing, but doing.
Its test is not logic, but result.
Its only authority is performance”
– Peter Drucker –
Si Fulan yang punya toko kelontong lelah hidup seadanya. Ia ingin agar dagangannya laris-manis, agar ia segera “naik kelas” menjadi orang kaya. Atas saran beberapa teman sekampung ia pergi ke sebuah dusun di kaki Gunung Lawu, menemui seorang dukun yang konon sakti mandraguna. Dukun itu merapal beberapa mantra. Tentunya ditingkahi oleh asap kemenyan dan suasana magis yang mencekam. Si Fulan juga dititahkan untuk mandi kembang tujuh rupa, di samping dioleh–olehi beberapa jenis jimat. Ternyata “proses” yang dijalani si Fulan memang ampuh. Tak berapa lama orang berbondong-bondong membeli dagangannya. Dapatkah dikatakan si Fulan telah menerapkan manajemen? Tentu tidak. Bukankah ia telah menempuh proses? Ya. Bahkan proses yang lumayan “serius” dan “berat.”
Namun proses bukanlah satu-satunya rambu manajemen. Ada rambu yang kedua, yaitu sistematis dan logis. Bisa saja, walaupun agak dipaksakan, dikatakan bahwa proses yang dilalui oleh Fulan bersifat sistematis. Namun bagaimanapun tidak logis. Logika ilmu pengetahuan, kecuali ilmu sihir tentunya, tidak dapat menjelaskan apa hubungannya merapal mantra, mandi kembang, mempersembahkan sesajian, atau menyimpan jimat, dengan perniagaan si Fulan yang jadi marak dan meriah. Bahkan sistematis pun sebenarnya tidak. Karena resep yang diberikan si mbah dukun kepada si Fulan konon tergantung pada apa yang dibisikkan para peliharaannya ketika si Fulan menghadap. Artinya, kalau di kemudian hari ada pasien lain, walaupun dengan kebutuhan yang sama, sangat boleh jadi si mbah akan menuturkan jalan keluar yang berbeda. Intinya, tak ada pola yang menghubungkan antara keluhan pasien dengan treatment yang diberikan. Dalam kacamata agama, perbuatan si Fulan adalah syirik. Dalam sudut pandang manajemen, ini lagi-lagi bentuk mismanagement!
Dalam kehidupan sehari-hari yang lebih umum kita lihat betapa banyak masalah, kekusutan, kekacauan, kesimpang-siuran yang membuat masyarakat kehilangan kebahagiaan, ternyata bersumber dari proses – bentuknya bisa berupa sistem, mekanisme, prosedur, aturan, dan lain-lain – yang tidak sistematis (baca: acak-acakan, melompat-lompat, tidak punya alur yang masuk akal), dan juga tidak cukup ditopang oleh dasar logika yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa waktu yang lalu saya punya tugas mengisi training di Surabaya. Sayangnya saya terlambat tiba di check-in counter Bandara Soekarno–Hatta karena taksi yang saya tumpangi mengalami pecah ban di jalan tol. Karena belum pernah mengalami hal tersebut sebelumnya, saya bertanya kepada petugas dari airline terkait mengenai apa yang semestinya saya lakukan. Hasilnya, saya pusing! Saya di ping-pong dari satu counter ke counter yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu loket ke loket yang lain. “Coba bicara pada Mbak yang di sana Pak.” “Coba ke loket reservasi Pak.” “Coba ke counter nomor 24 Pak.” Astagfirullah! Mbak yang bertugas di loket reservasi melayani saya dengan wajah galak, suara ketus, dan gaya setengah hati. “Pak, karena terlambat, jika Bapak ingin dimasukkan ke flight berikutnya Bapak terkena denda 75% dari harga tiket plus biaya up-grade sebesar sekian rupiah, sehingga totalnya sekian rupiah. Nanti dibayar di counter 24.” What?! Lebih dari dua kali lipat harga tiket saya sebelumnya!
Lalu, sesuai petunjuk si Mbak yang “pedas” itu saya kembali ke counter 24. Mbak yang ada di sana – paling tidak dia jauh lebih ramah – menanyakan berapa biaya tambahan yang dikenakan pada saya. Mendengar jumlah yang saya sebutkan, Mbak yang ramah itu berkata, “Wah, Bapak tidak perlu bayar sejumlah itu. Cukup setengahnya saja kepada kami. Di sini nama Bapak sudah saya tuliskan. Dan statusnya sudah saya buat CF (confirmed) untuk penerbangan berikut jam 13:30. Bapak tinggal datang. Sebutkan nama, bayar, dan berangkat.” Ajaibnya, pada saat saya datang lagi ke counter 24 menjelang pukul 13:30 “Miss Ramah” itu tak ada di sana, dan nama saya tidak tercantum di dalam daftar cadangan, apalagi dengan status confirmed. Macet bukan?! Alhasil, saya gagal berangkat ke Surabaya pada hari itu.
Mari kita bayangkan, apa derita umat, masyarakat, dan bangsa, jika mereka yang berada dalam posisi memimpin tidak punya kemampuan berpikir proses secara sistematis dan logis? Ya, mungkin mirip sekali seperti kondisi kita hari-hari ini.
“Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dari cara–cara yang sama.”
–anonimus–
Saya punya suatu kepercayaan sederhana mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Bagi saya, kualitas kepemimpinan seorang pemimpin diukur dari karya, bukan orasi atau wacana, walaupun kemampuan berorasi mungkin salah satu skill penting bagi pemimpin. Lihat saja pernyataan Allah SWT di dalam Al Qur-an: “Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu.’ Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” [QS. At-Taubah, 9: 105]
وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾
Simak juga peringatan keras Allah SWT di bagian lain dari Kitab Suci-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” [QS. Ash-Shaff, 61: 2-3]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾
Paradigma manajemen yang sehat merupakan modal dasar untuk mampu memimpin perubahan transformasional dengan sukses. Berpikir menggunakan manajemen membuat pemimpin mampu melaukiskan peta jalan (road map) perubahan yang akan mengantarkan komunitas yang dipimpinnya dari posisi here and now menuju the future dreamland. Kualitas berpikir manajemen pula yang akan dengan jelas membedakan cita-cita dari sekedar angan-angan, vision dari wish.
Tanpa kemampuan berpikir manajemen banyak pemimpin menjadi tak ubahnya sekedar orator atau filosof, bahkan provokator, yang trampil menuangkan mutiara pemikiran yang progresif-revolusioner dalam kata-kata bernas, baik dalam pidato yang menggelegar maupun tulisan yang menghujam, namun tak kunjung berhasil mewujudkan satupun gagasan hebat dalam realita komunitasnya. Ketika pemimpin model orator-filosof ini berpidato, orang-orang takjub terpana menyimaknya. Hati mereka tergetar. Mereka merasa fatwa-fatwa sang pemimpin mencerahkan pikiran dan menyegarkan semangat. Mereka terbang ke langit impian. Jantung mereka berdegup kencang. Darah mereka menggelora. Rasanya tak sabar lagi untuk menaklukkan dunia. Tapi apa jadinya ketika pidato itu selesai? Ketika mereka harus kembali ke dunia nyata? Saat mereka berhadapan lagi dengan realita yang kelewat jauh dari idealita? Mereka ibarat membentur tembok tinggi, atau bersua dengan jalan buntu, karena sang pemimpin tak kuasa menunjukkan peta jalan menuju negeri impian tersebut.
Betul bahwa pemimpin mesti visioner. Namun pemimpin juga harus transformatif, mampu mengurai visi tersebut menjadi sejumlah tonggak antara, seraya berperan sebagai sais yang memacu kuda-kudanya untuk menarik kereta berpindah dari satu tonggak ke tonggak berikutnya, demikian seterusnya, sampai tiba di terminal tujuan.
Di bagian sebelumnya telah kita diskusikan dua rambu yang pertama dalam manajemen, yaitu proses, serta sistematik dan logis. Apakah setiap proses yang tersusun dengan sistematik dan didasarkan atas suatu logika tertentu otomatis dapat disebut sebagai manajemen? Nanti dulu. Belum tentu. Perlu digarisbawahi bahwa pemimpin memanfaatkan manajemen, bukan tenggelam dalam kompleksitas manajemen.
Saya punya seorang teman. Sebut saja namanya Anto. Julukannya Mr. Sisdur, alias Tuan Sistem dan Prosedur, karena Anto memang serba teratur. Hampir semua hal dalam hidup Anto ada protokolnya, ada prosedurnya, dan hampir-hampir tak ada yang berubah. Namun Anto sering terlihat tidak bahagia. Keningnya sering berkerut. Mukanya ditekuk. Demikian itu ekspresi standarnya manakala berhadapan dengan situasi di luar perkiraannya. Kegandrungan pada sistem dan prosedur membuat Anto sama sekali kehilangan keluwesan menghadapi ketidakpastian.
Lebih seru lagi, sistem dan prosedur tersebut terus beranak-pinak semakin banyak. Kian hari kian tak jelas ujung pangkalnya. Misalnya, sesuatu dalam kamus Anto harus dikerjakan menurut prosedur A, namun kita ganti dengan cara B, dipastikan dia akan meledak alias marah besar. Jika kemudian kita bertanya, mengapa harus A dan tidak boleh B? Jawaban Anto, ya karena sudah begitu semestinya! The procedure has to be like that because it is the procedure! Macet total, ibarat jalur Pantura di musim lebaran.
Artinya, manajemen bukan sekedar proses yang sistematik dan logis. Ia juga harus ditujukan untuk mencapai pre-determined goal(s), tujuan, atau tujuan-tujuan, yang telah ditetapkan sebelum proses itu dimulai. Tujuan tersebut tentunya bukan begitu saja dipetik dari angin, melainkan diturunkan, diterjemahkan, juga secara sistematik dan logis, dari visi besar sang pemimpin.
Kesadaran dan penghayatan penuh mengenai tujuan inilah yang membuat pemimpin menjadi sosok yang dinamis, yang memadukan dua sisi yang seolah paradoksal. Di satu sisi ia sangat teguh – konsisten, konsekuen, dan presisten – dengan tujuan yang ingin dicapainya. Namun di sisi lain ia sangat lentur dalam memilih dan menentukan cara – termasuk sistem dan prosedur – yang diyakininya paling mungkin membantunya mencapai tujuan tersebut. Seperti seorang pengemudi. Mungkin menjadi tidak begitu penting mempersoalkan rute mana yang diambil – sejauh tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas tentunya – sepanjang mobil yang dikemudikan mampu memindahkan para penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan.
“Effectiveness is a habit; that is, a complex of practices. And practices can always be learned. Practices are simple, but always exceedingly hard to do well. They have to be acquired by practicing, and practicing, and practicing again.”
–Peter F. Drucker, 1967–
Karena cara bisa lebih dari 1001 banyaknya, dibutuhkan kriteria untuk memilihnya. Ini adalah rambu manajemen berikutnya. Cara yang dipilih mestilah yang efektif dan efisien. Nah, dua istilah ini tampaknya perlu mendapatkan porsi pembahasan agak luas. Demikian seringnya kata-kata “efektif dan efisien” digunakan dalam berbagai konteks, sehingga sering maknanya menjadi rumit dan tak jelas lagi, bahkan kadang-kadang agak konyol.
Ada pejabat atau pakar dalam wawancara televisi mengatakan, “cara itu memang efisien, namun tidak efektif.” Waduh! Bagaimana mungkin sesuatu bisa efisien jika tidak efektif? Meminjam istilah aljabar, efektifitas adalah necessary condition, sedangkan efisiensi adalah sufficient condition. Seluruh pilihan proses atau cara yang mampu mengantarkan kita pada tujuan disebut efektif. Dari berbagai alternatif proses atau cara tersebut, yang berbiaya paling rendah, adalah yang efisien.
Dalam urusan dengan action plan pribadi misalnya, banyak orang yang menuangkannya dalam bentuk bagan atau skema yang cantik dan canggih, dengan tampilan warna–warni memukau di gadget mereka. Namun seringkali keindahan dan kecanggihan itu menjadi tidak efektif karena tidak cukup disiplin untuk sering–sering merujuk pada action plan yang sudah mereka buat. Beruntung saya belajar dari guru manajemen saya, Taufik Bahaudin, tentang apa yang disebutnya stupid paper, sehelai kertas yang lusuh berlipat delapan, yang tak pernah luput dari saku kemeja beliau. Setiap terpikir ada sesuatu yang urgen untuk dilakukan, beliau tuliskan pada kertas itu. Sebaliknya, setiap ada to do thing yang selesai dikerjakan, beliau coret hal tersebut dari daftar.
Pernah saya bertanya pada beliau, mengapa harus kertas lusuh itu yang jadi tumpuan. Beliau kemukakan beberapa argumentasi. Pertama, ketika lembaran kumal itu dibuka, yang beliau lihat adalah sejumlah to do things yang menantang untuk diselesaikan, namun punya prioritas berbeda. Otomatis beliau terdorong untuk mencari mana to do thing yang paling urgen dituntaskan. Dengan bahasa yang sedikit canggih, kertas lusuh itu “memaksa” beliau berpikir logis dan sistematis. Tentu Anda ingat, ini rambu manajemen yang kedua.
Kedua, menurut beliau mencoret sebuah to do thing yang sudah berhasil dirampungkan punya kenikmatan psikologis yang sukar digambarkan dengan kata–kata dan bersifat addictive! Artinya, sensasi itu memprovokasi beliau untuk menuntaskan sejumlah to do things yang lain agar punya legitimasi untuk kembali mencoretnya dari daftar. Ketiga, mekanisme kertas lusuh itu, the stupid paper, begitu sederhana dan genuine. Implikasi, ketika menggunakannya kita fokus pada substansi, pada manfaatnya, dan tidak tergoda pada sejumlah kecanggihan “kosmetik” yang artifisial sifatnya.
Apakah jurus stupid paper ala Taufik Bahaudin itu efisien, itu perdebatan yang lain. Namun yang pasti ia menggambarkan efektifitas itu sama sekali tidak perlu rumit dan kelewat canggih. Disiplin pribadi adalah kata kuncinya.
Selanjutnya, bicara tentang efisiensi, tentunya berurusan dengan hitung–menghitung biaya. Namun perlu diingat, dalam menghitung biaya, bukan sekedar out-of-pocket expenses, biaya-biaya langsung yang dikeluarkan berupa uang kas. Harus diperhitungkan juga dengan cermat opportunity cost, nilai dari berbagai kesempatan dan peluang yang hilang, yang harus dikorbankan, jika kita memilih proses atau cara tersebut.
Harus dikalkulasi pula eksternalitas, yaitu berbagai kerugian yang diderita oleh pihak lain atau lingkungan jika kita menjalankan cara/proses tersebut. Contoh, sebuah pabrik sedang mempertimbangkan 2 alternatif cara pengolahan limbah, X dan Y. Cara X lebih mahal dibandingkan cara Y. Namun jika menggunakan cara Y yang lebih murah, limbah yang dihasilkan masih belum sepenuhnya aman bagi lingkungan. Jika demikian, pada saat menghitung biaya yang terkait dengan cara Y, harus diperhitungkan pula nilai kerugian yang timbul dari kerusakan lingkungan akibat limbah yang belum sepenuhnya aman tersebut. Dan jika itu dilakukan bisa jadi cara X lebih efisien, walaupun biaya langsungnya lebih mahal dibandingkan Y.
Bagaimana seseorang menyikapi eksternalitas tersebut disadari atau tidak juga membedakan “kasta” orang tersebut: apakah dia pemimpin sejati, atau sekedar eksekutif yang bekerja dengan kalkulasi bisnis jangka pendek. Pemimpin sejati punya tanggungjawab. Nilai itu tidak akan membiarkan dirinya mengambil keputusan apapun yang dampak sampingannya merugikan orang lain maupun lingkungan yang lebih luas. Buat pemimpin sejati, kebermanfaatan bagi manusia dan kemanusiaan adalah harga mati yang tak bisa ditawar.




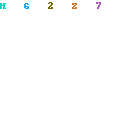


Tidak ada komentar:
Posting Komentar